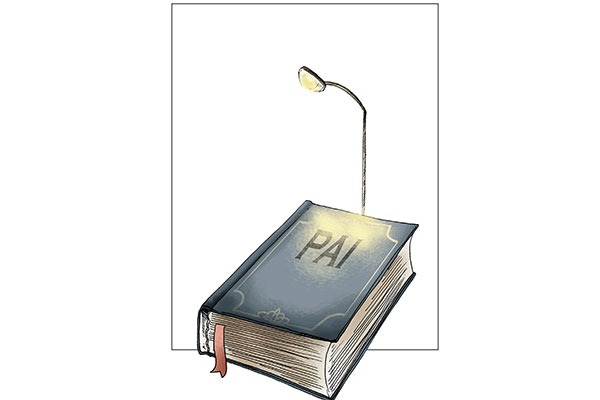
Penulis: Hatim Gazali
TEMPO hari, sejumlah grup Whatsapp dosen pendidikan agama Islam sempat dihebohkan cuplikan berita Setyono Darmono yang berisi tentang tidak perlunya pendidikan agama di sekolah. Karuan saja, para dosen langsung melontarkan kritik secara tajam.
Tak lama setelah itu, muncul juga pernyataan Menteri Agama bahwa tidak ada rencana penghapusan pendidikan agama. Bahkan, Setyono Darmono pun memberikan klarifikasi bahwa berita tersebut disalahtafsirkan. Sebaliknya, pendidikan agama yang diusulkan, menurutnya, justru harus diperkuat melalui penguatan pendidikan karakter.
Ini bukan kali pertama muncul cuplikan berita yang bernada provokatif ‘penghapusan pendidikan agama’. Sebelumnya, saat ide full-day school diembuskan Kemendikbud, muncul juga berita serupa; bahwa Kemendikbud akan menghapus pendidikan agama di sekolah dan mengembalikannya kepada pemangku pendidikan agama, seperti madrasah dan gereja.
Terhadap hal ini, ada dua hal yang bisa direfleksikan. Pertama, betapa kita sangat mudah terprovokasi berita tentang peniadaan pendidikan agama di sekolah. Tanpa perlu membaca berita secara menyeluruh, emosi kita segera naik ketika membaca sejumlah judul provokatif. Tentunya, ini juga berlaku terhadap isu-isu lain yang dibungkus dengan judul berita yang provokatif.
Kedua, dalam pengertian yang lebih mendalam, tidak sedikit di antara kita yang mempertanyakan perihal urgensi, manfaat, dan tujuan pendidikan agama di sekolah. Sejumlah pertanyaan kemudian menyeruak: apakah pendidikan agama berkontribusi terhadap pembentukan pribadi yang bertakwa sebagaimana yang dicita-citakan UU? Apakah pendidikan agama berhasil membentuk kesalehan individual dan sosial yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting dihadirkan untuk direfleksikan karena pendidikan agama sejatinya bukan hanya untuk membekali siswa dengan hafalan-hafalan doktrin agama, melainkan yang lebih penting ialah bagaimana mengimplementasikan ajaran-ajaran tersebut, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.
Problem pendidikan agama
Sejauh ini, pendidikan agama secara nasional dihadapkan pada sejumlah persoalan. Pertama, secara materi, pendidikan agama kita mengalami tumpang-tindih antartiap-tiap tingkat pendidikan. Apa yang diajarkan di sekolah menengah sering kali hanya bersifat repetisi sekolah dasar. Begitu seterusnya.
Kedua, bersifat doktriner. Sependek amatan penulis, pelajaran agama di sekolah dan perguruan tinggi lebih menitikberatkan pada rumusan-rumusan doktrinal agama. Siswa diminta untuk menghafal sejumlah ketentuan ajaran islam, seperti rukun iman, rukun Islam, syarat rukun salat dan haji, serta hafalan terhadap sejumlah teks agama, mulai ayat Alquran sampai pada hadis. Kajian yang lebih filosofis dan bermakna jarang disentuh para pendidik. Dengan hafalan ayat dan hadis yang dimiliki siswa, guru sudah merasa bahwa tujuan pendidikan agama Islam sudah tercapai.
Ketiga, metode pengajaran. Sebagai konsekuensi penempatan agama sebagai kajian doktriner, maka metode pengajaran yang dikembangkan guru sering kali menoton dan membosankan. Kreativitas guru sering kali dihadapkan pada dogma bahwa pendidikan agama harus serius. Karenanya, pendidikan agama harus disampaikan dengan metode yang doktriner, top-down, berbasis hafalan, dan miskin pertanyaan kritis.
Keempat, kompetensi dan profesionalisme guru. Di sejumlah lembaga pendidikan, yang mengajar agama Islam bukan ditentukan dari kualifikasi wawasan yang dimiliki, melainkan lebih kepada siapa yang tampak ‘saleh-salehah’ dengan ukuran yang sangat verbalistik, misalnya, ia sudah menunaikan haji.
Hambatan pendidikan karakter
Selain dari pada itu, tantangan lainnya ialah rendahnya kompetensi multikultural (multicultural competence) para pendidik. Studi yang dilakukan PPIM-UIN Syarif Hidayatullah (2016) mengonfirmasi hal ini. Ditemukan bahwa 81% guru pendidikan agama Islam (PAI) tidak setuju pendirian rumah ibadah agama lain di wilayahnya. Sebanyak 74% menolak memberikan ucapan selamat hari raya kepada penganut agama lain. Bahkan, ditemukan sebanyak 87,89% guru dan dosen yang menyatakan setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.
Atas dasar itulah, guru menyatakan tidak setuju jika PAI bertujuan membentuk siswa yang toleran dan berbuat baik kepada penganut Syiah (54,70%), Ahmadiyah (53,60). Mayoritas guru dan dosen PAI berpendapat bahwa materi PAI yang diberikan harus bertujuan menambah keimanan dan ketaqwaan siswa dan mahasiswa.
Dalam konteks ini, perlu disadari bahwa ukuran ketakwaan dan keimanan siswa lebih banyak diukur pada seberapa kuat hafalannya terhadap hukum Islam dan seberapa rajin ia melakukan ibadah. Sementara itu, toleransi, membangun kerukunan dengan intra dan antaragama yang merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam tidak masuk dalam indikator keimanan dan ketakwaan seseorang.
Jika pola pikir seperti ini terus dipelihara, rencana penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama (Islam, salah satunya) seperti yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, akan mengalami hambatan yang cukup serius. Alih-alih berkontribusi pada pembentukan mental yang compatible dengan kodrat zaman dan alam, pendidikan agama Islam justru berpotensi semakin menebalkan pola pikiran intoleransi di kalangan siswa dan mahasiswa.
Karena itulah, gerakan revolusi mental yang dicanangkan pemerintah harus dimulai dari revolusi cara pandang terhadap tujuan pendidikan agama, serta positioning pendidikan agama pada kurikulum pendidikan nasional, selain tentunya, peningkatan kompetensi multikulturalisme pendidik di semua jenjang pendidikan.
- Penulis adalah Dosen Universitas Sampoerna, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam (Adpisi)

















